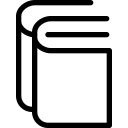EKSISTENSI DAN ESTETIK PENULIS SASTRA Naim Emel Prahana
EKSISTENSI DAN ESTETIK PENULIS SASTRA
Naim Emel Prahana
Di dalam karya sastra (tertulis) kaitan eratnya dengan bahasa telah secara berkelanjutan lahirnya obrolan tentang sastra akademik dan sastra populer sekian waktu silam sering dijadikan bahan polemik era kejayaan media cetak. Sampai peradaban teknologi merajai industri sosial sudah di level 5.0.0.10. obrolan itu perlahan mulai jarang terdengar dari masyarakat sastra Indonesia.
Eksistensi penulis sastra semakin banyak di era digital yang dirangkumkan di kawasan media sosial. Kepedulian dan ketidak pedulian terhadap ‘pengakuan’ terus berkembang masing-masing berinfiltrasi ke wilayah sebelah. Dari situ, muncullah makna ‘eksistensi’—dengan bahasa gaulnya sudah tidak lagi memakai makna definisi eksistensi itu sendiri. Paling-paling nyenggol—nyonggol sesaat atau beberapa saat. Sampai memenggal kata eksistensi menjadi eksis.
Eksis sekarang jadi bahasa populer, umum dan masuk ke arena semua profesi, sekedar menyebutkan kalimat ‘selalu’ ada; waktu, lokasi (keberadaan), keadaan dan ada. Ungkapan eksis ditampilkan ketika seseorang merespon orang yang dikenalnya di berbagai media penampilan. Khususnya media sosial (medsos). Bahasa gaul dan kalimat gaul ungkapan terasa akrab di telinga. Misalnya, “ woi eksis terus!”
Sebutan ungkapan itu dapat ditujukan kepada terjemahan keberadaan seseorang makin hari kian dikenal, jadi tenar atau populer. Kenapa dikatakan eksis (dari eksistensi), salahnya karena selalu terlihat dan realis (realitas) sekali. Dalam banyak pendapatan, eksis itu berseberangan dengan kata esensi yang menitik beratkan pada ‘ciri’. Kemudian menjelmalah kata eksistensi itu menjadi sempurna (ke – an: awalan dan akhirannya).
Jadi, benarlah kata ‘eksis’ itu tampilan (keberadaan) dan itu harus diciptakan, direncanakan agar sesuatu itu terlihat ada. Terlihat ada itulah yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa gaul—sosial ‘eksis’-nya diri seseorang menjadi dirinya sendiri. Oleh bahasa Indonesia eksistensi itu disebut ‘jati diri’. Ia tampil dan terlihat terus; apakah tulisan, karya maupun pembicaraannya terhadap sesuatu—katakanlah sesuatu itu adalah dunia sastra.
Menyingkat sedikit obrolan, dengan jati diri penulis sastra banyak hal yang mampu diberikan kepada bangsanya. Banyak hal yang dapat diperankan seorang penulis sastra—khususnya membentengi budaya bangsa terhadap pengaruh budaya asing yang terus melolong melalui dunia bisnis, industri, ilmu pengetahuan yang ‘selalu’ menggunakan istilah bahasa asing. Kemudian di Indonesia dipakai begitu saja tanpa mempelajari padanan katanya seperti kata ‘teknologi’.
Eksis—eksistensi seseorang (penulis sastra) akan menjadi motivator generasi berikutnya bukan karena format puisi, cerpen, novel, roman atau esay-esay. Atau karena gaya membacakan karya-karya sastra, tetapi karena dalam kosa kata yang dirangkum dalam kalimat karyanya sangat ori (asli) budaya (dan sastra) Indonesia. Mungkin disitulah peraih nobel banyak diperoleh oleh sastrawan bangsa lain. Bersebab, mereka menampilkan ‘jati diri’ manusia (bangsa) sendiri yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai media. Termasuk audio visual, kartun, komik, karikatur, visual atau juga gambar dengan caption yang menarik. Termasuk membuat cover ceritanya lebih aduhai.
Sebab lain, eksistensi itu bermakna lentur (kenyal), mengalami perkembangan-perkembangan. Bisa maju dan bisa juga mundur. Tergantung pada kemampuan penulis dalam mengaktualisasikan potensi budaya bangsanya sendiri (termasuk budaya ‘kearifan’ lokal—daerah).
Sisi lain, profesi sebagai penyair, cerpenis, novelis, romanis, teaterawan/dramawan, esais, kolomnis bukan profesi pelarian atau sampingan dan ada yang menyebut karena gagal di profesi lain akhirnya menjadi sastrawan. Bukan, bukan itu. Tapi, profesi di dunia sastra adalah profesi yang luar basa mulianya, hebat, bertalenta kuat dan sebagainya.
Dicontohkan dengan eksistensi (sebuah) keluarga. Keberlangsungan keluarga harus utuh agar terhindar dari ancaman eksisteni di luar eksistensi keluarga itu sendiri. Manusia terlebih dahulu bereksistensi, berjumpa, berkiprah di dunia dan baru sesudah itu mendefinisikan dirinya. Eksistensi diri penulis sastra itu akan berkembang terus mengolah potensi dirinya dengan kemampuan menerobos dan mengatasi batas-batas yang sebelumnya selalu “membelenggu dirinya”
Akan tetapi, ketika eksistensi penulis sastra itu diartikan di luar jalurnya karena sesuatu kepentingan. Baik kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan aliran dapat dipastikan eksisteni (jati diri) seorang penulis sastra akan tidak bermakna, kecuali bisnis kecil-kecilan. Eksisteni semakin menempa diri seorang penulis sastra, ia muncul, memilih keberadaan yang mampu mendorong kemampuan potensi yang mungkin masih terpendam.
Penulis sastra memilih untuk tetap hidup menghidupkan kehidupannya dengan cahaya harmonisasi berkomunikasi untuk menambah menormalkan dirinya menjadi aktual di tengah masyarakat apapun, serta dia mewujudkan kenyataan (autentik) dengan keberadaan dan sosio—jati dirinya. Oleh karena itu, penulis sastra umumnya tidak berada di lingkaran kekuasaan dan politik. Ia berada dan meng’ada’kan dirinya dalam dunia sesuai identitasnya sendiri.
Pengembangannya di dalam tahapan ‘proses’ terus menerus seseorang penulis sastra memiliki kehadiran (berada) dalam keadaan tertentu pada tempat dan waktu yang khusus (special). Dari tempat itulah ia menyentuh berbagai belahan kehidupan dengan berbagai karakter, sifat, budaya dan komunikasi masyarakat tertentu. Pengalamannya akan menjadi estetika yang luar biasa dapat diwujudkan dan dirasakan manfaat kenyamanan, ketentraman atau kedamaian bermakna luas.
Note: excitence (Inggris) or existere (latin)
Metro, 14 Juli 2024
Subscribe to Literanesia
Get the latest posts delivered right to your inbox